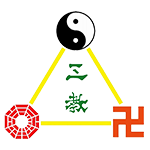Kwee Tek Hoay
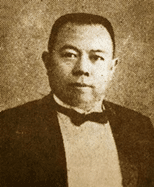
Kwee Tek Hoay dilahirkan di Bogor, 31 Juli 1886 dan meninggal tanggal 4 Juli 1952 di Cicurug, Bogor, Jawa Barat. Ia adalah sastrawan Indonesia peranakan Tionghoa yang banyak menulis tentang kehidupan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Novelnya yang terkenal adalah Boenga Roos dari Tjikembang. Kwee adalah anak bungsu dari pasangan Kwee Tjdiam Hong dan Tan An Nio. Kedua orang tuanya imigran berasal dari desa Lam An, Provinsi Fujian, daratan Tiongkok. Mereka datang dan menetap di Bogor sebagai pedagang. Di samping bekerja sebagai pedagang obat-obatan yang dibawa dari daratan Tiongkok, ayah Kwee Tek Hoay juga membuka usaha pengobatan tradisional Tionghoa (sinshe) bersama beberapa orang temann
Pada tahun 1894 Kwee Tek Hoay masuk ke sekolah Tionghoa tradisional yang menggunakan bahasa Hokkian sebagai bahasa pengantar. Dia mengalami kesulitan mengikuti pelajaran karena tidak memahami bahasa Hokkian, Sebagai akibatnya, dia sering bolos dari sekolah. Kwee lebih banyak membantu ayahnya dalam berdagang dengan cara ikut menjajakan dagangan (tekstil) dari rumah ke rumah.
Dia belajar bahasa Belanda dari seorang wanita Belanda dan belajar bahasa Inggris dari seorang wanita India. Penguasaan kedua bahasa asing itu sangat bermanfaat baginya dalam membaca bahan penulisan. Kwee Tek Hoay sebenarnya ingin belajar di sekolah Belanda, tetapi ia tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda sehingga keinginannya itu tidak terwujud.
Setelah remaja, ia mulai menggeluti dunia usaha (dagang). Di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa di Bogor, ia dikenal sebagai pedagang yang ulet. Dia mempunyai usaha (toko) serba ada di Bogor. Meskipun perhatiannya tercurah pada usahanya, ia masih sempat menyisakan waktunya untuk memikirkan persoalan yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan Tionghoa.
Kwee Tek Hoay menikah pada umur 20 tahun dengan gadis peranakan Tionghoa, Oei Hiang Nio. Dia membina istrinya dalam usaha dagang sehingga sangat membantu usahanya. Di samping berhasil membina rumah tangganya secara harmonis, Kwee juga sangat telaten dalam menjaga hubungan dengan kakaknya, Kwee Tek Soen, Kwee Wan Nio, dan Kwee Sui Nio. Secara bergotong-royong, mereka bersama-sama mengelola usaha keluarga.
Kwee mulai aktif menulis pada tahun 1905, dan fokus utama perhatiannya adalah masalah kemasyarakatan. Tulisannya dimuat dalam surat kabar Li Po, Bintang Betawi, dan Ho Po. Pada saat terjadi Perang Dunia II, ia menulis sebuah artikel yang berjudul “Pemandangan Perang Dunia I tahun 1914—1918” dimuat di Sin Po. Kwee pernah menjabat sebagai Dewan Redaksi majalah Li Po dan Ho Po. Pada tahun 1926 Kwee mendirikan majalah Panorama. Akan tetapi, ia menjual majalah itu pada tahun 1931 dan menerbitkan majalah Moestika Romans dan Moestika Dharma. Setelah mendirikan kedua majalah itu, perhatian Kwee lebih tertumpu pada persoalan filsafat, agama, kebatinan, dan sejarah. Di samping itu, ia juga aktif menyebarkan ajaran tiga agama (Sam Kauw) dan mendirikan perkumpulan Sam Kauw. Kwee Tek Hoay menyelenggarakan dialog tentang Agama Budha antara Josiast Van Dienst dan Bhikshu Lin Feng Fei (Kepala Klenteng Kwan Im Tong) di Prinseniaan (Jl. Mangga Besar). Hasil dialog tersebut antara lain berisi pernyataan bahwa Klenteng sebagai tempat ibadah umat Buddha tidak hanya digunakan untuk tempat pemujaan saja, tetapi juga sebagai tempat untuk mendapatkan pelajaran Agama Buddha.
Dunia sastra mulai digelutinya sekitar tahun 1905 ketika menulis novel pertamanya berjudul Yashuko Ochida atawa Pembalesannja Satoe Prampoean Japan. Naskah itu diterbitkan secara bersambung dalam majalah Ho Po, Bogor. Tahun 1919 ia menulis drama 6 babak Allah jang Palsoe. Drama itu diterbitkan atas biaya Tjiong Koen Bie sebanyak seribu eksemplar. Drama Allah jang Palsoe menyuarakan kecaman terhadap keserakahan manusia yang sangat mementingkan harta di atas segala-galanya. Pemujaan terhadap harta mengalahkan kecintaan terhadap Tuhan. Drama ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas. Pada saat itu banyak kelompok sandiwara
yang mementaskan drama Allah yang Palsoe dalam berbagai kesempatan.
Dia ikut menyemarakkan kehidupan sastra Indonesia, terutama pada periode awal, dengan menghasilkan karya-karya yang bernuansa pembauran. Novel, drama, dan syair ciptaannya menyuarakan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekitarnya. Meskipun ide ceritanya lebih menonjolkan budaya Tionghoa, Kwee Tek Hoay menyesuaikan cerita itu dengan keadaan Indonesia.
Secara umum, gagasan yang tertuang dalam karyanya merupakan masalah kemasyarakatan Tionghoa pada zamannya. Realitas yang berkembang dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia banyak mengilhami Kwee dalam berkarya.
Masalah pembauran yang tertuang dalam Boenga Roos dari Tjikembang merupakan realitas yang hidup di tengah-tengah masyarakat keturunan Tionghoa. Tentang pandangan ini, Kwee sempat berpolemik dengan kelompok Sin Po yang cenderung menganggap keturunan Tionghoa sebagai orang asing di Hindia Belanda yang harus menggunakan bahasa Hokkian sebagai bahasa pertama. Dia tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dia berpandangan lebih moderat. Menurut Kwee, orang-orang Tionghoa adalah kawula Hindia Belanda yang harus berbahasa Melayu atau Barat sebagai bahasa pertama, tetapi memegang teguh tradisi Tionghoa.
Di samping banyak mengungkapkan persoalan yang ada di lingkungan masyarakat keturunan Tionghoa, karya-karyanya juga menyentuh berbagai persoalan yang menyangkut masyarakat lain di luar kelompok Tionghoa, terutama masyarakat pribumi.
Kwee juga banyak menerjemahkan syair dan buku-buku agama. Dia menerjermahkan Rubayat karya Umar Khayam. Di samping itu, tulisannya tentang keagamaan, antara lain, adalah Hikayat Kong Hoe Coe, Agama Boedha di Jawa pada Zaman Koeno, Bhagawad Gita, dan Keterangan Ringkas tentang Agama Islam.
Sumber: ensiklopedia.kemdikbud.go.id